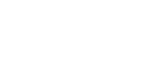Oleh : Josephin Kaila Tyara Prasetyo, Universitas AKI
Pada bulan Oktober lalu, kota Semarang kembali menelan kenyataan pahit: banjir besar yang merendam berbagai titik kota Semarang. Banjir ini melumpuhkan aktifitas warga. Mulai dari Genuk, Kaligawe, Tlogosari, hingga sebagian ruas Pantura tergenang air yang cukup dalam dan hanya trukbesar saja yang berani untuk melewati jalanan tersebut. Hujan yang turun beberapa jam saja sudah cukup membuat mobil berhenti, rumah terendam, dan warga terjebak dalam kecemasan yang seolah datang rutin setiap tahun. Pertanyaannya, sampai kapan kita menerima takdir ini?
Ini bukan sekadar karena curah hujan yang tinggi. Memang benar, cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Namun kita tidak boleh menyalahkan hujan saja. Banjir yang terjadi di Semarang adalah akumulasi tentang persoalan: penurunan muka tanah (land subsidence) setiap tahun, buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan, hingga penumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Kombinasi faktor inilah yang membuat air tak lagi punya ruang untuk kembali ke tanah.
Penurunan muka tanah di kawasan pesisir timur Semarang mencapai beberapa sentimeter tiap tahun. Ketika tanah tenggelam lebih cepat daripada naiknya permukaan air laut, genangan menjadi konsekuensi logis. Sementara itu, pembangunan pembangunan yang terus dikejar justru banyak mengorbankan ruang terbuka hijau dan wilayah resapan yang ada di daerah pesisir kota Semarang.
Situasi ini diperburuk oleh kondisi drainase yang tidak berfungsi maksimal. Pemerintah memang mengerahkan pompa portabel dan petugas untuk membersihkan saluran di wilayah Kaligawe, tetapi banjir tetap membutuhkan waktu lama untuk surut. Penanganan sementara tersebut menunjukkan bahwa sistem drainase di kawasan pesisir timur Semarang belum mampu menampung debit air besar dalam waktu singkat. Permasalahan ini tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi hampir berulang setiap musim hujan.
Pengulangan Siklus yang Sama.
Yang paling menyedihkan bukan hanya banjir itu sendiri, tetapi pola yang terus terulang setiap tahun nya yaitu: banjir → bantuan logistik → perbaikan sementara → diabaikan oleh pemerintah → banjir lagi.
Pemerintah memang melakukan normalisasi dan penanganan, tetapi selama akar masalah tidak disentuh, kita hanya memoles permukaan. Banjir ini tejadi setiap tahun, namun pemerintah kota Semarang belum bertindak tegas untuk permasalahan banjir ini.
Ketika tanah mengalami penurunan, daerah tersebut otomatis menjadi cekungan dan lebih mudah tergenang. Kondisi ini masih diperparah oleh sedimentasi sungai dan penyempitan alur air di bagian hilir.
Pemerintah sebenarnya telah membangun beberapa kolam retensi untuk membantu menampung limpasan air, namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Pada beberapa kejadian, kolam retensi memang membantu menurunkan ketinggian air, tetapi pada hujan dengan intensitas lebih tinggi, kolam tersebut tidak cukup menampung seluruh debit air. Bahkan, sejumlah warga menilai bahwa kolam retensi di beberapa titik tidak lagi berfungsi optimal karena kurangnya perawatan.
Jika melihat dampaknya di Kaligawe—mulai dari kerugian ekonomi, kerusakan rumah, kesehatan warga, hingga lumpuhnya jalur transportasi nasional—maka jelas bahwa banjir bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan masalah struktural yang harus segera diselesaikan. Kaligawe adalah contoh paling nyata bagaimana ketidaksiapan sistem tata kota menghadapi perubahan iklim dan pertumbuhan urban. Selama akar persoalan tidak disentuh, khususnya penurunan muka tanah, perbaikan drainase, dan pengelolaan air, maka di setiap musim hujan warga Kaligawe akan terus menghadapi ancaman yang sama.