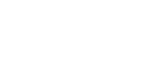Oleh: Emma Perbina Br Sembiring
Mahasiswa Pendidikan Matematika
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)
Domisili: Kabanjahe / Singaraja
Email: emmaperbina24@gmail.com
Sebagai remaja yang sedang menempuh pendidikan tinggi, saya merasa prihatin sekaligus tergugah oleh insiden intoleransi yang terjadi baru-baru ini di Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan retret pelajar Kristen yang dihadiri anak-anak usia 10 sampai 14 tahun dibubarkan secara paksa oleh sekelompok warga. Kegiatan rohani yang seharusnya damai berubah menjadi pengalaman penuh tekanan, simbol keagamaan dirobohkan, dan peserta kecil yang seharusnya dilindungi justru mengalami ketakutan.
Sebagai generasi muda yang hidup di tengah keberagaman Indonesia, saya melihat bahwa kejadian seperti ini bukan hanya masalah satu wilayah atau satu kelompok. Ini adalah masalah kita bersama. Masalah yang mencerminkan betapa pendidikan toleransi belum sepenuhnya menyentuh hati dan pikiran masyarakat, bahkan di era digital seperti sekarang.
Banyak dari kita, para remaja, tumbuh dalam lingkungan yang mungkin kurang memberi ruang untuk berdialog dengan perbedaan. Kita hidup dalam “gelembung sosial” yang cenderung membentuk persepsi bahwa apa yang berbeda dari kita adalah sesuatu yang salah atau bahkan mengancam. Padahal, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila, perbedaan adalah kekayaan yang harus dipahami, bukan dihindari.
Kasus Sukabumi menjadi bukti bahwa intoleransi bisa terjadi bahkan kepada anak-anak. Ini sangat menyedihkan. Karena itu, saya percaya, sudah saatnya pendidikan toleransi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman nyata, diskusi kritis, dan pergaulan lintas latar belakang sejak remaja.
Sebagai pelajar, saya punya harapan besar terhadap sistem pendidikan kita. Beberapa hal yang bisa kita dorong bersama:
1. Kurikulum yang Mengajarkan Toleransi dengan Cara yang Relevan
Jangan hanya belajar definisi toleransi. Mari kita belajar memahami cerita orang lain, agama lain, dan budaya lain. Ajak siswa berdialog tentang kasus nyata seperti yang terjadi di Sukabumi, bukan hanya sekadar menghafal sila-sila Pancasila.
2. Guru dan Sekolah Sebagai Ruang Aman
Sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk berdiskusi dan berekspresi. Guru perlu dilatih agar bisa menjadi fasilitator yang adil, tidak menghakimi perbedaan keyakinan, dan aktif melibatkan semua siswa dalam diskusi lintas nilai.
3. Proyek Kolaboratif Antar Sekolah
Coba bayangkan, jika sekolah-sekolah dari latar belakang berbeda mengadakan proyek sosial bersama. Bisa berupa kerja bakti, diskusi terbuka, atau festival keberagaman. Hal ini akan membuka mata kita semua bahwa kita bisa bekerja sama tanpa harus sama.
4. Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi
Kita, para remaja, menghabiskan banyak waktu di media sosial. Kenapa tidak digunakan untuk menyebarkan narasi damai? Akun edukasi, konten toleransi, hingga kampanye digital bisa dimulai dari kita. Mari kita lawan ujaran kebencian dengan edukasi dan konten positif.
Sebagai remaja Indonesia, saya percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Dari berani berteman dengan orang yang berbeda agama. Dari mendengarkan cerita yang berbeda dari yang biasa kita dengar. Dari menyadari bahwa kita semua memiliki hak yang sama untuk hidup damai di tanah air ini.
Toleransi bukan soal setuju atau tidak setuju. Ini soal menghargai. Soal mengakui bahwa setiap orang punya hak untuk menjalani keyakinannya dengan damai. Dan kita, generasi muda, punya peran besar dalam memastikan bahwa Indonesia masa depan adalah tempat yang lebih aman, lebih ramah, dan lebih adil bagi semua.
Mari jadikan insiden Sukabumi sebagai titik balik, bukan luka yang terulang. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari sekolah kita, dan dari cara kita melihat perbedaan.